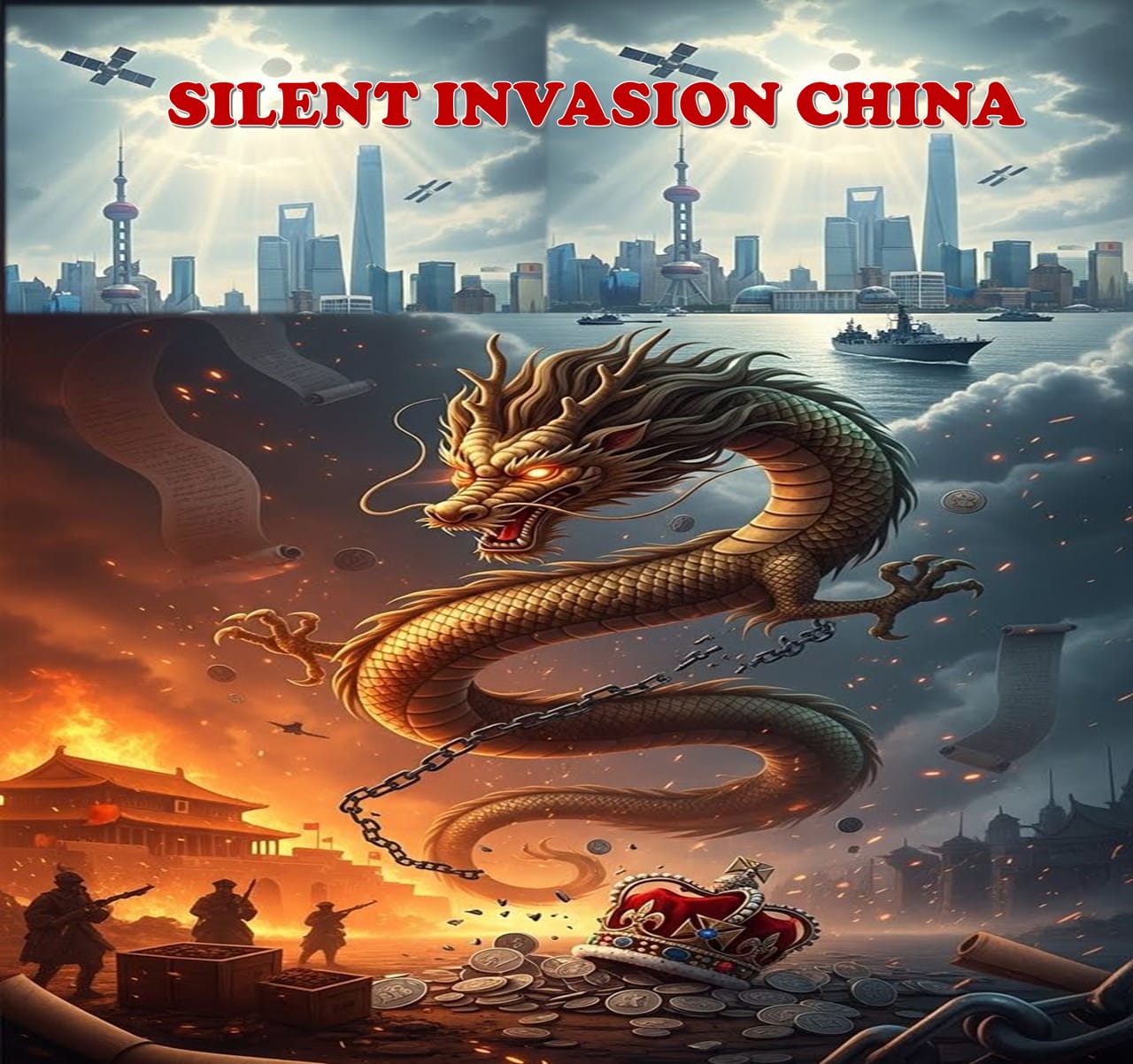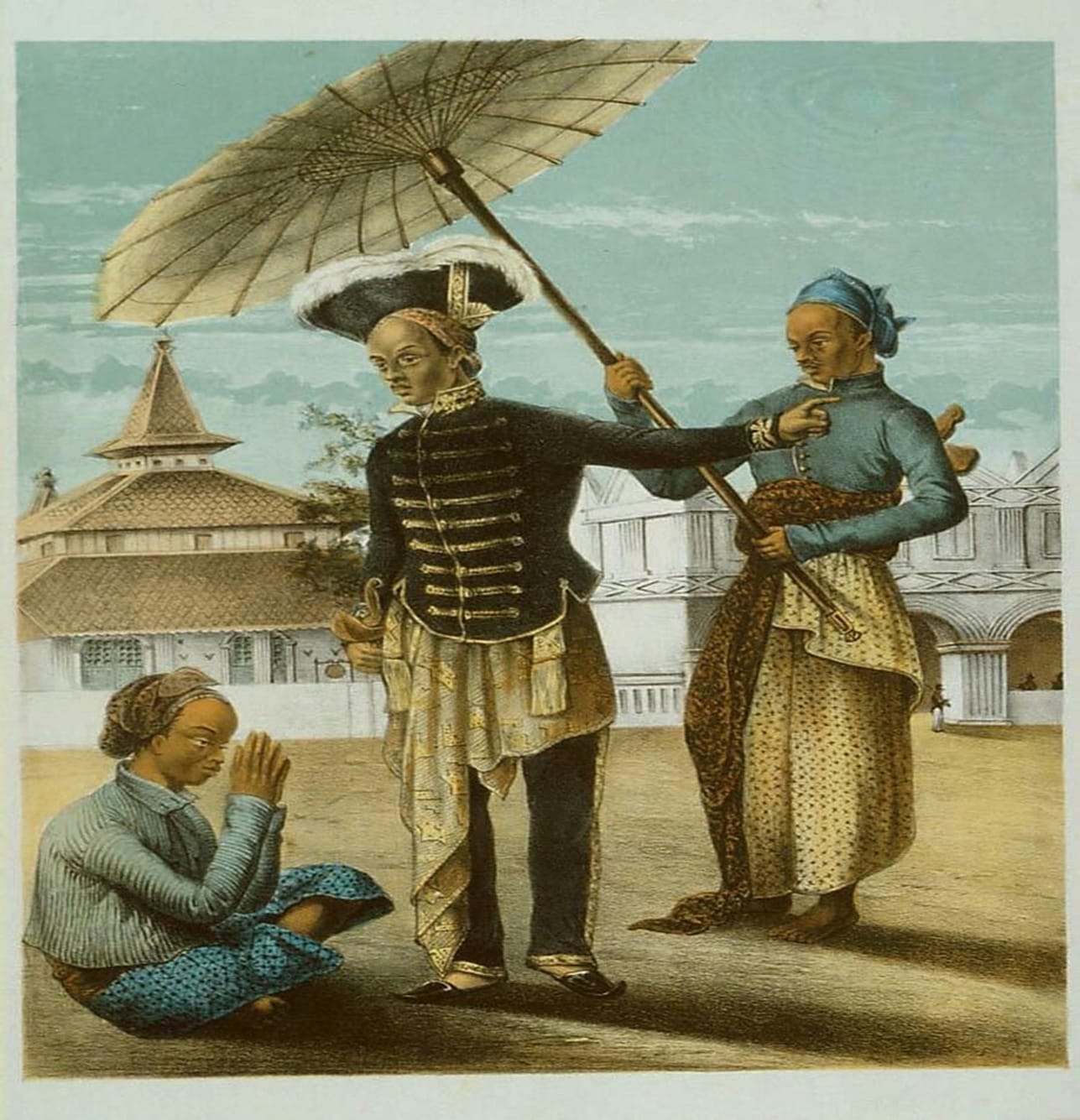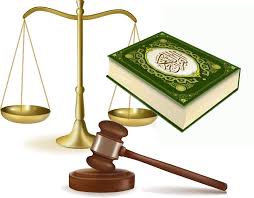(Oleh: Muhammad Taufiq Nabil, Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta)
‘Kota Pelajar’—sebuah julukan yang melekat erat dalam benak masyarakat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Yogyakarta? Yogyakarta memiliki peran historis, kultural, dan institusionalnya dalam dunia pendidikan. Setiap tahun, ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru nusantara datang untuk menimba ilmu di kota yang dijuluki sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan ini. Deretan kampus ternama, suasana yang kondusif untuk belajar, serta biaya hidup yang dianggap terjangkau menjadikan Yogyakarta sebagai tempat yang ideal untuk belajar. Namun, seiring berjalannya waktu, julukan itu mulai menggugah tanya: benarkah kota ini memberi ruang belajar yang setara bagi seluruh warganya, ataukah gelar ‘Kota Pelajar’ hanyalah mahkota yang dikenakan oleh segelintir kalangan saja?
Dalam sebuah diskusi yang dimoderatori oleh Kamaluddin, ia membuka pembahasan dengan merujuk pada temuan dari Pers Mahasiswa Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Menurut laporan mereka, ratusan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat tidak bersekolah, bahkan sebagian di antaranya terpaksa putus sekolah.
Data yang dihimpun memperlihatkan pola fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, terdapat 161 kasus anak putus sekolah. Angka ini sempat menurun menjadi 101 kasus di tahun 2018, namun kembali naik menjadi 104 pada 2019. Tahun 2020 mencatat angka yang nyaris sama, yakni 102 kasus. Lonjakan drastis terjadi pada 2021, saat jumlah kasus mencapai puncaknya di angka 365.
Yang paling memprihatinkan, jenjang pendidikan menengah atas—terutama SMA dan SMK—menjadi penyumbang terbesar dalam kasus putus sekolah ini. Ironis, mengingat jenjang ini seharusnya menjadi batu loncatan menuju perguruan tinggi.
Di sudut-sudut kota yang jauh dari gemerlap kampus besar, masih ada anak-anak yang harus menempuh jarak berkilo-kilometer hanya untuk sampai ke sekolah. Di balik deretan gedung megah dan seminar ilmiah, masih tersembunyi ruang-ruang kelas yang reyot dan minim fasilitas. Sementara pelajar dari berbagai penjuru negeri bisa mengejar mimpi di kampus ternama, duduk di ruang kelas ber-AC, menikmati akses internet tanpa hambatan, banyak anak lain belajar di ruang yang dindingnya lapuk, dengan cahaya seadanya dan buku-buku yang usang. Mereka menghafal bukan hanya pelajaran, tapi juga keterbatasan.
Selain banyaknya siswa yang putus sekolah, Yogyakarta juga masih tersimpan praktik yang mencederai semangat pendidikan yang adil dan terbuka—yakni pungutan liar terselubung di sekolah-sekolah. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat bahwa praktik semacam ini masih marak terjadi, terutama dengan kemasan yang rapi: “sumbangan sukarela” dari orang tua murid.
Menurut Muhammad Rifki, Asisten Pemeriksa Laporan ORI DIY, pihaknya telah menerima lebih dari satu laporan masyarakat terkait pungutan yang dilakukan oleh sekolah melalui komite. Meski diberi label “sumbangan”, praktik ini memiliki ciri khas pungutan: adanya nominal tertentu, batas waktu pembayaran, dan sifatnya yang tidak benar-benar sukarela.
Dana yang terkumpul umumnya digunakan untuk berbagai kebutuhan di luar kegiatan belajar-mengajar inti—seperti pembangunan gedung, pengadaan fasilitas, hingga program-program nonreguler. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah tidak dibenarkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun kepada orang tua siswa.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Robani Iskandar dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY). Ia menyebut, praktik pungutan berdalih sumbangan bukan lagi hal asing di lingkungan sekolah negeri di DIY. Sekolah kerap menyebutnya “sumbangan”, tetapi dalam pelaksanaannya menetapkan jumlah pasti dan tenggat waktu—dua hal yang mengubah sukarela menjadi kewajiban diam-diam.
Di balik julukan “Kota Pelajar”, data ini menjadi cermin bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengecap pendidikan. Bagi sebagian keluarga, bertahan hidup menjadi prioritas yang tak jarang harus ditebus dengan mengorbankan masa depan pendidikan anak.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal gedung sekolah atau gaji guru, melainkan tentang siapa yang diberi peluang dan siapa yang dibiarkan tertinggal. Maka, saat Yogyakarta dielu-elukan sebagai Kota Pelajar, bisakah kita benar-benar menyebutnya demikian jika tak semua anak mendapat tempat yang sama untuk bermimpi?