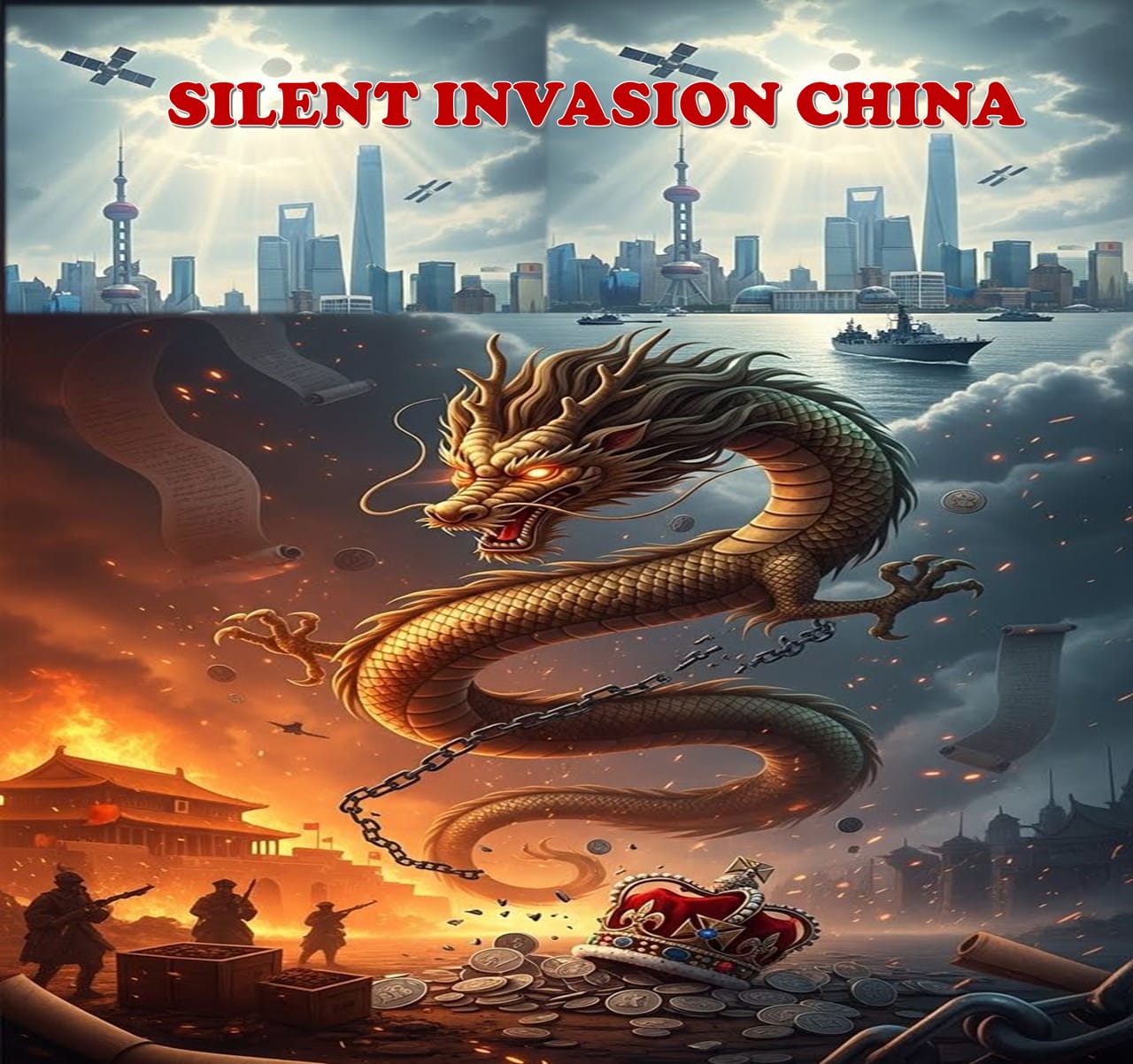(Oleh: Delky Nofrizal Qutni – Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Aceh Selatan, Wakil Ketua DPW APRI Aceh)
Dalam setiap lembar sejarah Aceh, kekhususan selalu menjadi kata kunci yang menggambarkan hubungan istimewa antara daerah ini dengan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, rakyat Aceh memperoleh ruang otonomi yang luas, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Namun, perjalanan kekhususan itu tampak terus diuji oleh dinamika regulasi nasional, yang sering kali berjalan di atas semangat sentralisasi.
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu ujian paling mutakhir bagi kekhususan Aceh. Regulasi ini menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merevisi UU Minerba, dengan penegasan baru mengenai pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. PP tersebut mempertegas kendali pemerintah pusat dalam seluruh rantai pengelolaan tambang, mulai dari penetapan wilayah, izin usaha, hingga pengawasan kegiatan eksplorasi dan produksi.
Dalam konteks nasional, PP 39 tahin 2025 diharapkan menghadirkan standardisasi tata kelola tambang yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan. Namun bagi Aceh, regulasi ini justru menimbulkan pertanyaan besary sejauh mana kekhususan daerah ini masih bisa diimplementasikan dalam kerangka hukum yang semakin terpusat?
Aceh hingga kini belum memiliki qanun yang secara khusus mengatur pertambangan rakyat (WPR) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kondisi ini menyebabkan Aceh mau tidak mau harus sepenuhnya merujuk langsung pada PP 39 tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM tentang pedoman teknis penyusunan WPR dan WIUP untuk BUMD/Ormas. Secara administratif, langkah tersebut memang diperlukan untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum. Namun secara politis dan filosofis, ia mengandung dilema, dimana kekhususan yang diperjuangkan melalui darah dan perjanjian damai justru berpotensi tereduksi menjadi kepatuhan administratif semata.
Kekhususan Aceh seharusnya tidak berhenti pada status simbolik. Dalam konteks tambang, UU Pemerintahan Aceh (UUPA) dengan jelas memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengelola SDA di wilayahnya. Pasal 156 hingga 160 UUPA tersebut menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan tambang diberikan kepada Pemerintah Aceh, dengan mekanisme yang dapat diatur melalui qanun. Artinya, Aceh memiliki peluang hukum untuk menafsirkan dan menyesuaikan regulasi nasional sesuai dengan karakter sosial, ekonomi, dan lingkungan daerahnya sendiri.
Sayangnya, peluang itu belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini, belum ada Qanun Pertambangan Rakyat yang menjadi dasar operasional bagi lahirnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Aceh. Akibatnya, instruksi Gubernur Aceh tentang percepatan pengusulan WPR yang sejatinya sangat mulia untuk kedaulatan ekonomi rakyat, berpotensi terjebak dalam ranah simbolik belaka. Tanpa dokumen teknis, peta geologi, dan administrasi sesuai pedoman nasional, usulan WPR hanya akan menjadi simulakra, yakni bayangan dari realitas yang belum pernah benar-benar ada.
Dari Kekhususan Menuju Kedaulatan
Dalam teori sosial Jean Baudrillard, simulakra menggambarkan kondisi ketika representasi menggantikan realitas. Dalam konteks Aceh, simulakra kekhususan bisa muncul ketika narasi “otonomi khusus” hanya hidup dalam pidato dan dokumen, namun tak berdaya menghadapi logika regulasi nasional. Padahal, Aceh memiliki ruang legal yang cukup untuk menunjukkan kemandiriannya, asal berani menegakkan kembali marwah kekhususan itu dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur.
Secara yuridis, PP 39 tahun 2025 memang mempertegas peran pemerintah pusat, tetapi tidak menutup ruang bagi daerah berstatus khusus seperti Aceh untuk mengatur wilayah tambang yang luasnya di bawah 5.000 hektare. Berdasarkan semangat kekhususan yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, pemerintah provinsi sebenarnya memiliki kewenangan menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di bawah ambang batas tersebut, selama tetap diintegrasikan dengan sistem nasional.
Artinya, Pemerintah Aceh tidak harus menunggu instruksi teknis dari Kementerian ESDM semata. Dengan payung hukum kekhususan, Aceh bisa menetapkan WPR sendiri tentunya melalui pendekatan ilmiah, data geologi, serta partisipasi masyarakat. Langkah itu bukan bentuk pembangkangan terhadap pusat, melainkan aktualisasi dari semangat desentralisasi yang diakui konstitusi.
Jika kebijakan WPR benar-benar dijalankan dengan serius, maka dampaknya akan jauh melampaui aspek ekonomi. Pertama, ia akan menegakkan kembali marwah keadilan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal. Kedua, ia membuka ruang bagi pemberdayaan masyarakat penambang tradisional yang selama ini berada di pinggir hukum. Ketiga, ia memperkuat posisi Aceh dalam percaturan politik nasional, bahwa kekhususan bukan sekadar anugerah, melainkan tanggung jawab historis yang harus diwujudkan dalam tata kelola nyata.
Namun untuk mewujudkan itu, Pemerintah Aceh tidak cukup hanya mengandalkan retorika. Dibutuhkan langkah teknokratis yang konkret: penyusunan peta geologi dan wilayah prospektif tambang rakyat, inventarisasi data potensi, kajian lingkungan, serta dokumen administratif sesuai format nasional. Semua itu harus dirangkai menjadi satu dokumen teknis pengusulan WPR yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.
Peran lembaga seperti Dinas ESDM Aceh, akademisi, dan organisasi yang bergerak di bidang penambang rakyat menjadi sangat strategis. Mereka bisa menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi, antara idealisme kekhususan dan realitas administratif. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan menentukan apakah kekhususan Aceh tetap hidup sebagai ruh otonomi, atau sekadar simbol politik yang kehilangan makna.
Data menunjukkan, aktivitas pertambangan rakyat di Aceh telah tersebar di banyak kabupaten, terutama di Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya. Sebagian besar berlangsung tanpa legalitas formal, sehingga rentan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Legalitas melalui penetapan WPR akan menghadirkan kepastian hukum sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan yang ramah lingkungan.
Lebih dari itu, WPR bisa menjadi instrumen keadilan ekonomi. Di tengah dominasi perusahaan besar yang menguasai ribuan hektare wilayah tambang, kehadiran WPR merupakan manifestasi dari ekonomi kerakyatan yang diamanatkan UUD 1945. Dalam hal ini, kekhususan Aceh seharusnya menjadi pelindung bagi rakyat kecil, bukan sekadar payung bagi birokrasi.
Kekhususan juga memikul tanggung jawab moral. Ia harus membuktikan bahwa Aceh mampu mengelola SDA dengan lebih arif, transparan, dan berkeadilan dibandingkan wilayah lain. Maka, ketika pemerintah pusat menuntut integrasi data dan sistem, Aceh perlu menjawab dengan kesiapan dokumen, bukan dengan resistensi kosong. Integrasi bukan ancaman terhadap otonomi, melainkan cara untuk memastikan kekhususan itu diakui dalam sistem nasional.
Pada akhirnya, pertarungan antara kekhususan dan sentralisasi tidak harus berakhir dengan pertentangan. Ia bisa menjadi dialektika menuju kematangan otonomi. PP 39 tahun 2025 memang menuntut kepatuhan terhadap standar nasional, tetapi dalam kerangka hukum Aceh, kepatuhan itu dapat ditafsirkan sebagai kesetaraan, bukan subordinasi.
Aceh pernah menjadi pusat peradaban, tempat di mana hukum, agama, dan kedaulatan berpadu membangun marwah rakyatnya. Kini, di tengah kompleksitas regulasi modern, marwah itu kembali diuji. Jika kekhususan dibiarkan menjadi simulakra, Aceh akan kehilangan arah, tetapi jika kekhususan dimaknai sebagai panggilan untuk berdaulat secara hukum, ilmiah, dan moral, maka PP nomor 39 tahun 2025 bukan ancaman, melainkan peluang untuk meneguhkan kembali identitas Aceh di panggung nasional.
Kekhususan Aceh tidak boleh berhenti sebagai narasi sejarah. Ia harus hidup dalam kebijakan konkret, dalam setiap dokumen WPR, setiap peta geologi, setiap izin yang berpihak kepada rakyat. Menegakkan marwah kekhususan bukan berarti menolak regulasi pusat, melainkan memastikan bahwa dalam setiap aturan nasional, masih ada ruang bagi Aceh untuk menjadi dirinya sendiri. Sebab kekhususan yang kehilangan ruhnya hanyalah bayangan dan seperti setiap simulakra, ia tampak nyata, tetapi sejatinya kosong.