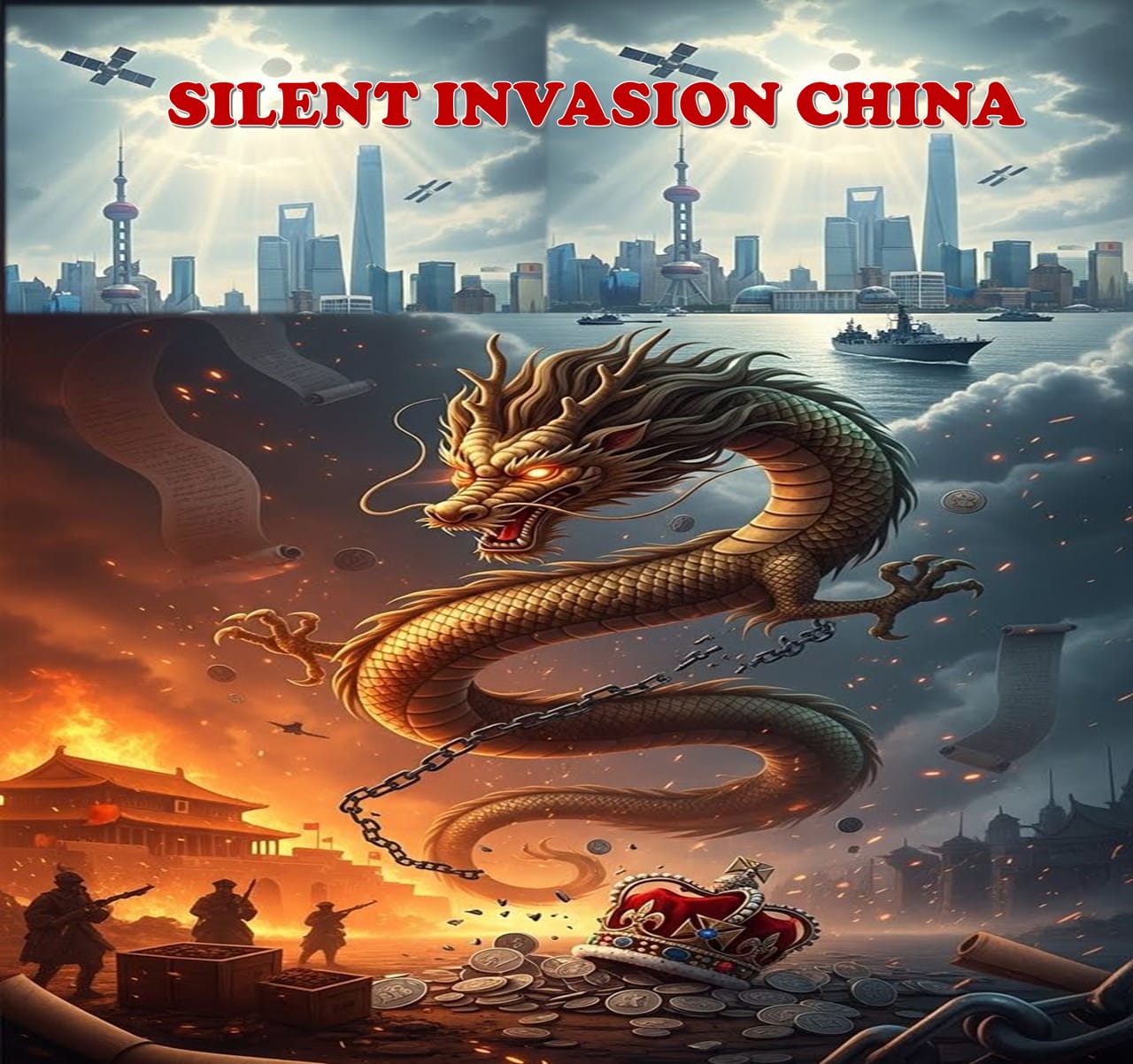(Tista Sari, Mahasiswa Prodi Hukum UPN Bukittinggi)
Desentralisasi merupakan semangat reformasi yang melahirkan otonomi daerah, memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bidang yang diserahkan ke daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan dan pengelolaan koperasi. Namun, akhir-akhir ini muncul kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kembali urusan koperasi melalui program bernama Koperasi Merah Putih, yang diprakarsai oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Program ini menargetkan pembentukan koperasi berbadan hukum nasional di seluruh desa di Indonesia dalam waktu cepat, dengan struktur, nama, dan sistem yang seragam dari pusat.
Kebijakan ini menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan asas rekognisi yang menjadi dasar hukum desa. Ketika koperasi yang seharusnya tumbuh dari kebutuhan masyarakat justru dibentuk secara top-down, maka makna partisipasi warga dan kearifan lokal dikhawatirkan terpinggirkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah pemerintah pusat sedang mendorong pemberdayaan ekonomi desa, atau justru melangkahi kewenangan daerah dan desa?
Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang dibangun atas dasar semangat kekeluargaan dan partisipasi anggota. Dalam konteks desa, koperasi seharusnya menjadi cerminan dari kebutuhan dan potensi lokal, bukan sekadar proyek birokratik. Namun, program Koperasi Merah Putih justru memaksa setiap desa mendirikan koperasi dengan nama, logo, sistem, hingga struktur organisasi yang seragam dan ditentukan dari atas. Ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan karena dinilai mengabaikan asas subsidiaritas, yaitu prinsip bahwa urusan publik sebaiknya diserahkan pada level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat.
Dalam hukum Indonesia, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggarisbawahi hak desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat.
Dengan adanya kebijakan koperasi seragam dari pusat, semangat otonomi dan rekognisi ini tampak dikesampingkan. Pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM seakan mengambil alih peran desa, bahkan dalam urusan yang sangat lokal seperti pendirian koperasi. Hal ini tidak hanya menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, tetapi juga memperlemah partisipasi masyarakat desa dalam merumuskan kebutuhan ekonominya sendiri.
Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Jika kebijakan koperasi ini dilihat sebagai bagian dari substansi hukum, maka harus diakui bahwa strukturnya sangat sentralistik. Bahkan dari sisi budaya hukum, masyarakat desa bisa merasa asing dan tidak memiliki ikatan emosional dengan koperasi yang dibentuk tanpa keterlibatan mereka secara utuh.
Lebih jauh, dalam kacamata teori negara kesejahteraan (welfare state), negara seharusnya memfasilitasi pemberdayaan rakyat, bukan sekadar membentuk institusi baru tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Koperasi seharusnya menjadi alat pemerataan kesejahteraan yang hidup dari bawah, bukan kendaraan proyek politik atau pencitraan birokrasi.
Bahkan Ombudsman Republik Indonesia pernah mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan pusat tanpa konsultasi yang cukup dengan pemangku kepentingan lokal dapat menimbulkan maladministrasi dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Kritik juga muncul dari berbagai kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, termasuk peneliti bidang hukum tata pemerintahan, yang menilai pendekatan seragam seperti ini berisiko menghilangkan keberagaman sosial-budaya desa serta bertentangan dengan prinsip pemerintahan berbasis partisipasi lokal.
Menurut pendapat saya, kebijakan Koperasi Merah Putih justru berpotensi melemahkan semangat otonomi desa yang telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Alih-alih mendorong pemberdayaan yang berakar dari potensi lokal, pendekatan seragam dari pemerintah pusat ini cenderung mengabaikan keberagaman karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi tiap desa di Indonesia. Padahal, desa merupakan entitas yang unik dan memiliki kearifan lokal yang seharusnya menjadi dasar dalam merancang strategi pembangunan, termasuk dalam pembentukan koperasi.
Saya menilai bahwa keberhasilan koperasi desa tidak bisa ditentukan hanya melalui keseragaman struktur atau logo, melainkan harus bertumpu pada partisipasi aktif warga desa, rasa memiliki, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Ketika semua aspek koperasi dipaksakan dari atas, tanpa melibatkan warga sebagai subjek utama, maka risiko kegagalan program akan semakin besar. Selain itu, hal ini juga menggerus rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa sekadar menjadi objek kebijakan, bukan mitra pembangunan.
Negara seharusnya memfasilitasi dan mendampingi desa untuk membangun koperasi yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan mereka sendiri. Intervensi yang terlalu jauh justru mengarah pada sentralisasi kekuasaan, yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan semangat desentralisasi yang telah diperjuangkan. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar lebih menghargai kedaulatan desa, serta menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan secara nasional dengan pendekatan sentralistik menjadi ancaman nyata bagi semangat desentralisasi dan otonomi desa di Indonesia. Alih-alih memberdayakan masyarakat desa, pendekatan top-down seperti ini justru memperlemah prakarsa lokal dan menjauhkan koperasi dari prinsip kekeluargaan yang menjadi jiwanya. Negara seharusnya berperan sebagai fasilitator, bukan direktur tunggal. Upaya penguatan ekonomi desa hanya akan berhasil jika berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan menghargai kearifan lokal sebagai fondasi utama pembangunan.
Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan semacam ini, agar prinsip negara hukum dan keadilan sosial tetap terjaga. Pemerintah harus kembali pada semangat awal reformasi: menyerahkan urusan rakyat kepada rakyat sendiri melalui pemerintahan daerah dan desa yang berdaulat.