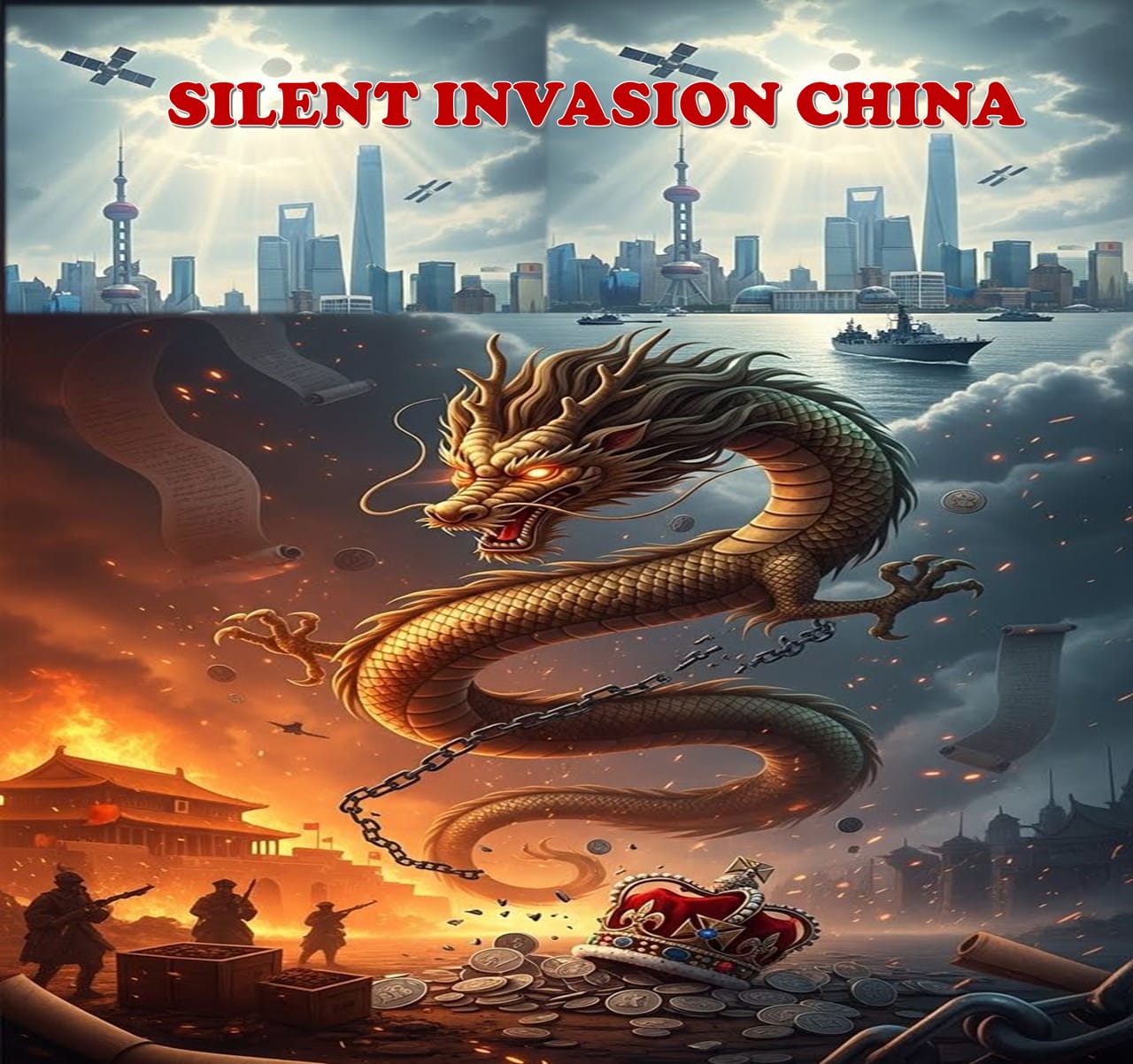(Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen)
Reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dipromosikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum nasional. Produk ini diklaim sebagai penanda berakhirnya warisan hukum kolonial, dengan fondasi filosofis Pancasila serta orientasi pemidanaan modern yang menekankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Secara normatif, KUHP dan KUHAP baru disebut hendak menghapus diskriminasi, dualisme hukum, serta ketimpangan relasi kuasa dalam sistem peradilan.
Namun, klaim normatif tersebut berhadapan langsung dengan realitas praksis penegakan hukum yang justru bergerak ke arah sebaliknya. Alih-alih menjadi instrumen emansipasi keadilan, hukum kerap tampil sebagai mekanisme politik untuk melayani kepentingan kekuasaan dan oligarki ekonomi. Di titik inilah adagium klasik lex est quod populus iubet atque constituit, yakni hukum sebagai kehendak rakyat justru kehilangan maknanya, digantikan oleh hukum sebagai kehendak elite.
Fenomena tersebut mencapai intensitas paling problematik pada era pemerintahan Joko Widodo, terutama ketika penegakan hukum berjalan beriringan dengan menguatnya peran politik Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Duet kekuasaan eksekutif dan aparat penegak hukum ini membentuk konfigurasi relasi kuasa yang oleh sebagian publik dipersepsikan sebagai regresi demokrasi pascareformasi.
Memori kolektif publik mencatat bagaimana revisi Undang-Undang KPK secara sistematis melemahkan independensi lembaga antikorupsi. Laporan Transparency International Indonesia dan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperkuat kesan bahwa agenda pemberantasan korupsi mengalami kemunduran struktural. Pada saat yang sama, perluasan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Polri, berlangsung tanpa diimbangi mekanisme akuntabilitas yang memadai.
Di sektor ekonomi-politik, lahirnya omnibus law, revisi Undang-Undang Minerba, serta berbagai regulasi pro-investasi mencerminkan keberpihakan negara pada akumulasi modal skala besar. Negara tampil sebagai fasilitator kepentingan oligarki, sementara prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 kian terpinggirkan. Dalam konteks ini, hukum kehilangan fungsi etiknya dan menjelma sekadar instrumen legitimasi kebijakan ekonomi-politik yang elitis.
Lebih jauh, institusi-institusi demokrasi mengalami degradasi fungsi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, justru terseret dalam pusaran konflik kepentingan yang merusak kepercayaan publik. DPR, sebagai representasi kedaulatan rakyat, sering kali tampil sebagai pemberi stempel kebijakan eksekutif. Sementara itu, praktik represif aparat terhadap kritik dan oposisi sipil memperlihatkan gejala authoritarian legalism, sebagaimana dikonsepsikan oleh Kim Lane Scheppele, yakni penggunaan hukum untuk melanggengkan kekuasaan.
Dalam perspektif sejarah, pola ini mengingatkan pada praktik kolonial Belanda yang memadukan kekuatan koersif dan kooptasi elite lokal melalui politik balas budi. Kekuasaan dijaga bukan semata dengan represi, tetapi juga dengan distribusi privilese, promosi jabatan, dan impunitas hukum. Relasi kekuasaan dibangun melalui loyalitas personal, bukan institusi yang sehat. Inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “kolonialisme gaya baru” yang berlindung di balik retorika demokrasi dan pembangunan.
Akibatnya, masyarakat mengalami disorientasi etik. Standar benar dan salah menjadi relatif, berubah mengikuti kepentingan politik yang dominan. Dalam psikologi sosial, kondisi ini dikenal sebagai moral disengagement, ketika publik kehilangan pegangan nilai akibat inkonsistensi penegakan norma oleh negara. Warisan etika politik para pendiri bangsa yang menempatkan kekuasaan di bawah hukum dan moral kian tergerus.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika politik nasional masih dibayangi tuntutan publik untuk melakukan koreksi mendasar atas warisan kekuasaan sebelumnya. Seruan untuk mengadili pelanggaran kekuasaan masa lalu, mengganti pimpinan Polri, serta melakukan perombakan kabinet mencerminkan akumulasi kekecewaan publik. Namun, kebijakan yang diambil sejauh ini justru menunjukkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan elitis, alih-alih radical break yang dijanjikan dalam kampanye.
Dalam teori legitimasi Max Weber, kekuasaan tidak cukup hanya berdiri secara legal-formal; ia harus diyakini dan diterima secara moral oleh masyarakat. Ketika negara tetap berjalan tetapi kepercayaannya terkikis, legitimasi memasuki fase rapuh. Di titik ini, simbolisme politik, pidato persatuan, dan kosmetika kebijakan tidak lagi memadai.
Presiden Prabowo dihadapkan pada pilihan historis, yaitu melanggengkan toleransi terhadap standar ganda hukum dan warisan otoritarian, atau mengambil langkah berani untuk memulihkan keadilan substantif.
Sejarah menunjukkan, persatuan nasional tidak lahir dari pembungkaman kritik, melainkan dari keberanian negara menegakkan hukum secara adil, setara, dan berintegritas.
Di tengah carut-marut tata kelola bernegara, satu pelajaran mendasar tetap relevan bahwa kekuasaan yang abai pada keadilan pada akhirnya akan kehilangan legitimasi. Negara tidak boleh sekadar bekerja untuk citra, melainkan untuk memulihkan kepercayaan rakyat melalui keberpihakan nyata pada hukum dan keadilan.