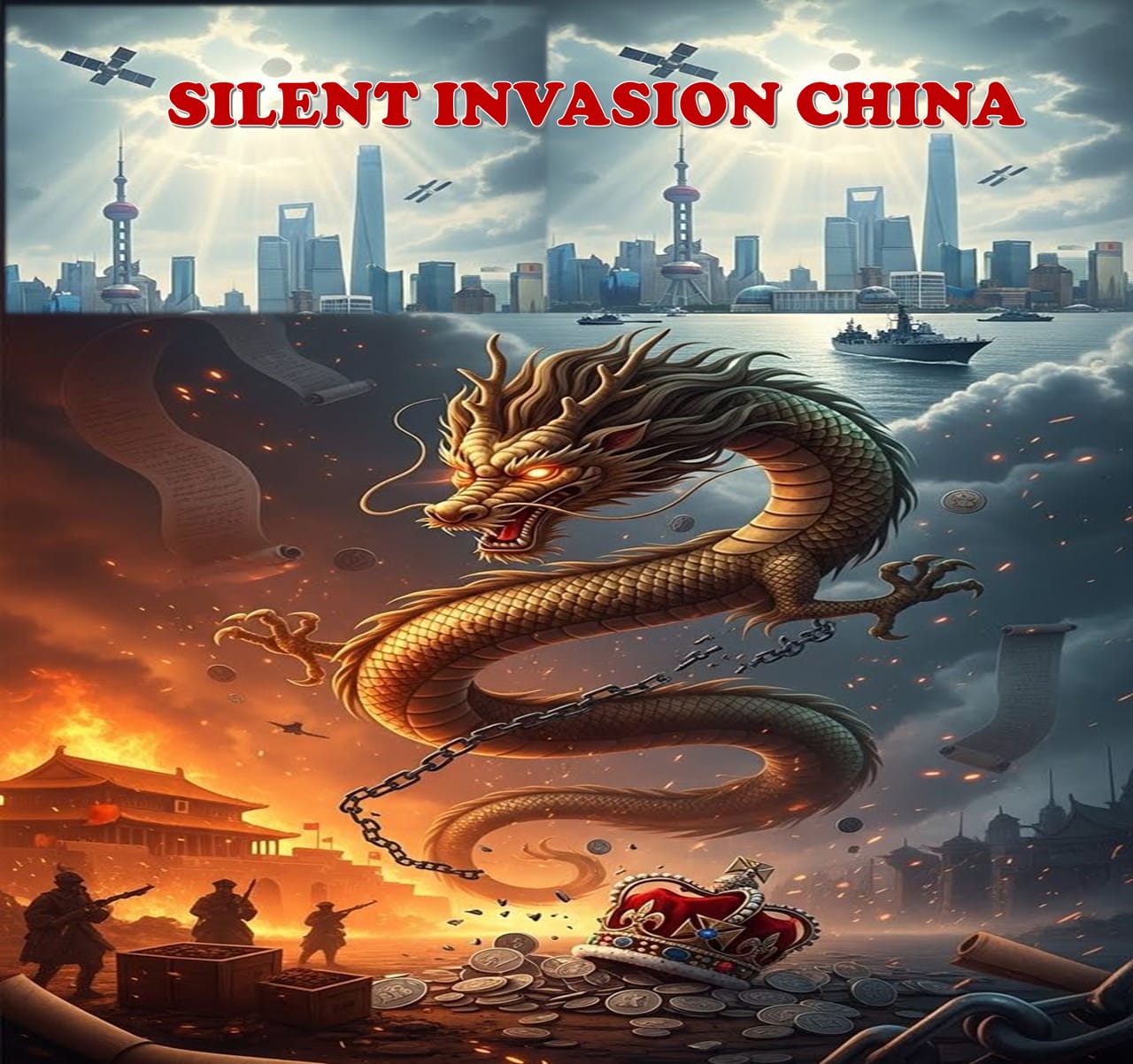(Oleh: Sri Radjasa, M.BA, Pemerhati Intelijen)
Pergantian presiden semestinya menjadi momentum pembaruan. Rakyat berharap hadirnya arah baru, keberanian menata ulang kekuasaan, serta koreksi terhadap praktik pemerintahan yang selama satu dekade terakhir dipandang problematik. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dipersepsikan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama Presiden Joko Widodo. Alih-alih memutus mata rantai patronase, negara seperti melanjutkan pola yang sama dengan aktor berbeda.
Sejak awal pembentukan kabinet, publik dibuat bertanya-tanya. Kabinet yang terbentuk sangat gemuk dan sarat kompromi politik. Banyak wajah lama kembali mengisi jabatan strategis, sebagian di antaranya menyisakan catatan persoalan hukum dan etik. Penentuan posisi kekuasaan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif, melainkan lebih menyerupai upaya menjaga keseimbangan elite dan mengamankan dukungan politik. Dalam konteks ini, kekuasaan terasa elitis, menjauh dari denyut kepentingan rakyat.
Dalam kajian demokrasi, kondisi semacam ini berbahaya. Demokrasi memang masih berjalan secara prosedural, dimana pemilu tetap dilaksanakan, lembaga negara tetap berfungsi, namun substansinya mengalami kemunduran. Kritik publik kerap dianggap sebagai gangguan stabilitas, sementara oposisi dilemahkan melalui konsolidasi kekuasaan. Negara berisiko berubah menjadi arena bagi segelintir elite, bukan ruang pengabdian bagi kepentingan rakyat.
Janji pemberantasan korupsi yang menjadi bagian penting dari Asta Cita Prabowo–Gibran sejauh ini belum menunjukkan hasil yang meyakinkan. Penegakan hukum terkesan selektif. Pergantian pejabat atau aparat di lapangan terjadi, tetapi aktor-aktor utama tetap aman. Korupsi tidak dibongkar sebagai kejahatan sistemik, melainkan dikelola agar tidak mengguncang fondasi kekuasaan.
Data Indonesia Corruption Watch mencatat, sepanjang 2016 hingga 2023 terdapat sedikitnya 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan kerugian negara mencapai Rp64 triliun. Fakta ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Revisi UU BUMN pada Februari 2025 membuka jalan bagi pembentukan Danantara, sebuah entitas yang dinilai minim transparansi dan diberi kekebalan hukum tertentu. Dalam negara hukum, kebijakan semacam ini jelas mengundang tanda tanya besar.
Berbagai produk hukum bermasalah yang lahir di era sebelumnya,seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba, bukan hanya dipertahankan, tetapi diperluas. Revisi UU Minerba terbaru bahkan memperlihatkan bagaimana hukum dijadikan alat politik patronase, untuk merawat jejaring dukungan kekuasaan. Ketika hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan instrumen kepentingan, kepercayaan publik pun runtuh.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap abai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika aturan turunan justru mengangkangi putusan MK dan didorong untuk dilegalkan, maka wibawa konstitusi dipertaruhkan. Dalam sistem demokrasi, kepatuhan terhadap konstitusi bukan pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, negara akan meluncur ke arah kekuasaan yang sewenang-wenang.
Presiden Prabowo kerap menekankan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan dan menyebut Presiden Jokowi sebagai “guru politik”. Namun keberlanjutan tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran atas kekeliruan. Seorang pemimpin yang berjiwa negarawan justru dituntut berani melakukan koreksi, meski berisiko secara politik. Ketika loyalitas personal lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat dan supremasi hukum, maka kepemimpinan kehilangan legitimasi moralnya.
Fenomena yang kini populer disebut sebagai “Indonesia Gelap” bukan sekadar ungkapan emosional. Ia mencerminkan rasa frustrasi publik atas meredupnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Yang tampak adalah konsolidasi kekuasaan yang semakin tertutup, ditopang oleh kolaborasi elite politik, aparat, dan kekuatan ekonomi rente. Negara terasa semakin jauh dari rakyatnya.
Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa kekuasaan yang menutup diri dari kritik tidak pernah bertahan lama. Reformasi 1998 lahir ketika rakyat menyadari bahwa negara telah menyimpang terlalu jauh dari amanat konstitusi. Hari ini, tanda-tanda kegelisahan itu kembali muncul. Demokrasi memang tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan, ketika kegelapan dibiarkan tanpa koreksi.
Rakyat Aceh dan Indonesia pada umumnya mencintai kedamaian. Namun sejarah juga mencatat, ketika keadilan dan kedaulatan terus diabaikan, kesadaran kolektif rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Negara seharusnya belajar dari sejarah, sebelum bayang-bayang kekuasaan lama benar-benar menelan masa depan bangsa.