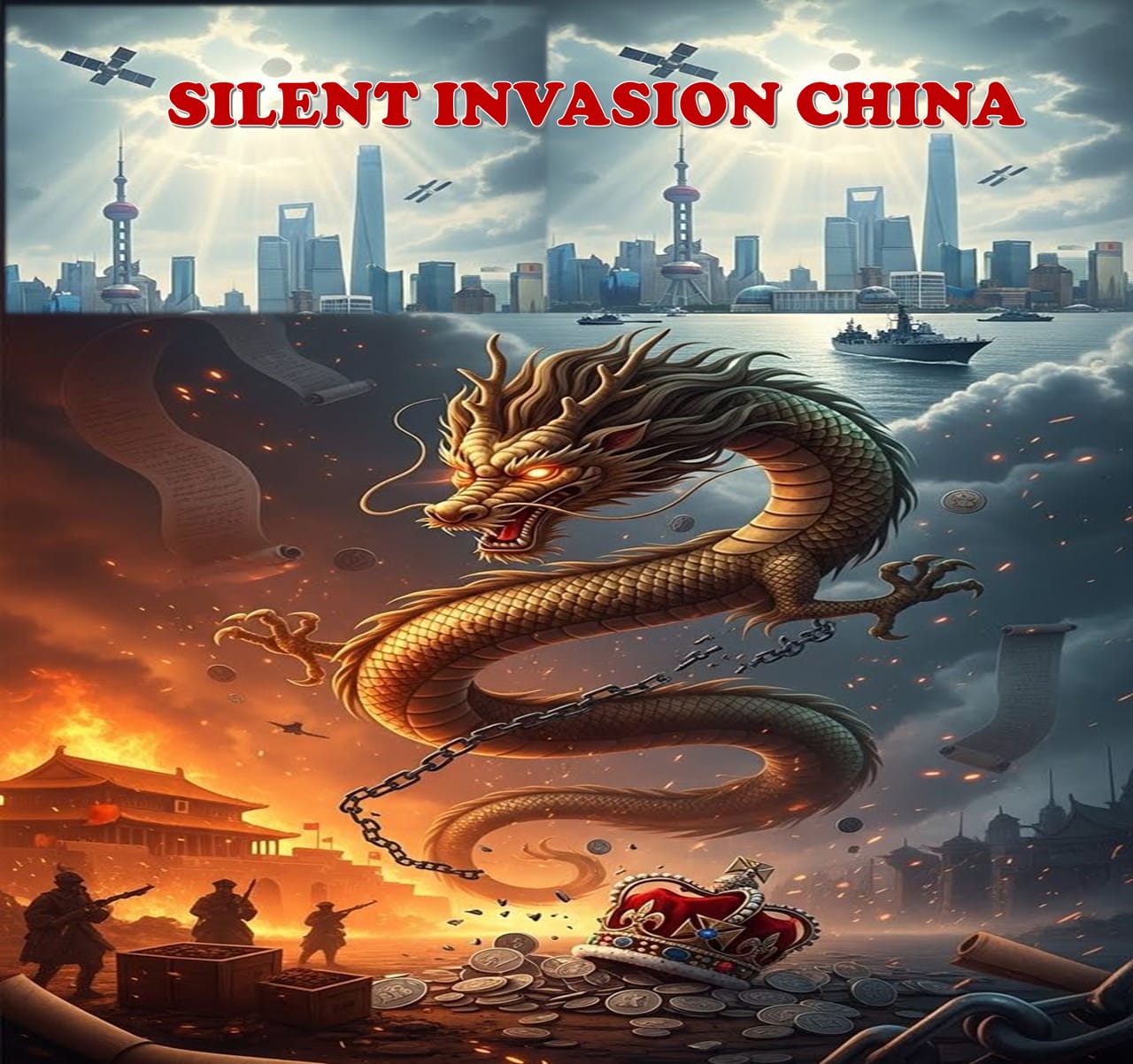(Oleh: Hanzirwansyah, Ketua Pandawa Lima Aceh Selatan)
Dalam lintasan hidup sosial yang semakin rumit, manipulasi kini tak lagi datang dengan wajah garang. Ia hadir dalam bentuk senyum, empati palsu, dan sanjungan yang tampak tulus namun berujung pada penguasaan halus atas pikiran orang lain. Dunia modern, termasuk kehidupan sosial di tanah Aceh, telah menjelma menjadi gelanggang halus di mana niat disembunyikan dalam kabut kepentingan. Di tengah kabut itulah, ketenangan batin menjadi kekuatan yang paling langka, sekaligus paling mahal.
Di Aceh, yang dikenal dengan nilai-nilai adat dan syariat yang kental, masyarakat terbiasa memuliakan sopan santun dan menjaga perasaan orang lain. Namun dalam praktiknya, kesantunan yang tidak dibarengi kesadaran diri sering menjelma menjadi jebakan. Banyak orang berkata “ya” agar dianggap saleh, mengalah agar tetap diterima, dan tersenyum demi harmoni semu. Padahal, kebaikan yang lahir dari ketakutan kehilangan penerimaan bukanlah kebaikan, melainkan keterikatan. Dan keterikatan adalah celah paling empuk bagi manipulasi.
Filosofi Aceh sebenarnya telah lama mengajarkan tentang keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Dalam hikayat-hikayat lama, orang Aceh digambarkan sebagai ulee seunara, hatee meuhom (kepala yang berpikir jernih, hati yang teguh memegang nilai). Namun, modernitas seringkali membuat banyak di antara kita kehilangan “hatee meuhom”-nya. Kita menjadi rapuh oleh citra, terseret oleh validasi, dan mudah tersulut oleh narasi yang menggoda perasaan.
Padahal, ketenangan sejati tidak lahir dari keramaian tepuk tangan, tetapi dari kejernihan dalam memahami niat, baik niat diri sendiri maupun orang lain. Orang yang tenang bukanlah yang tak terusik, melainkan yang mampu menatap badai dengan pandangan terang. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, kapan harus berkata “tidak” dengan hormat, dan kapan harus diam dengan bermartabat.
Dalam psikologi modern, kondisi ini disebut emotional sovereignty yaitu kedaulatan emosi. Dalam filsafat kehidupan Aceh, ia sepadan dengan “meuadab” dalam pengertian yang utuh yakni tahu tempat, tahu batas, tahu arah. Ketika seseorang sudah mencapai titik ini, ia tak lagi mudah digiring oleh rasa bersalah, diperalat oleh iba, atau diseret oleh pujian. Ia berdaulat atas dirinya, bukan karena keras kepala, tapi karena paham nilai yang ia jaga.
Lihatlah bagaimana banyak konflik sosial, bahkan di tingkat lokal, berawal dari manipulasi kecil yang tumbuh menjadi ketegangan besar. Dalam politik, birokrasi, maupun hubungan sosial, permainan niat seringkali lebih berbahaya dari serangan langsung. Ia merusak kepercayaan, mengaburkan niat baik, dan menumpulkan kesadaran kolektif. Maka yang dibutuhkan Aceh hari ini bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi rakyat yang tenang yang mampu melihat jernih di balik kabut kepentingan.
Menjadi tenang di tengah kabut niat orang lain bukan berarti menyerah pada keadaan. Itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena di dunia yang dipenuhi kebisingan, orang yang mampu mendengar bisikan nuraninya sendiri adalah orang yang benar-benar merdeka.
Dan di situlah, sebagaimana filosofi Aceh mengajarkan, nilai manusia diukur bukan dari seberapa keras ia bersuara, melainkan seberapa jernih ia bertahan menjaga nurani di tengah badai kepentingan.